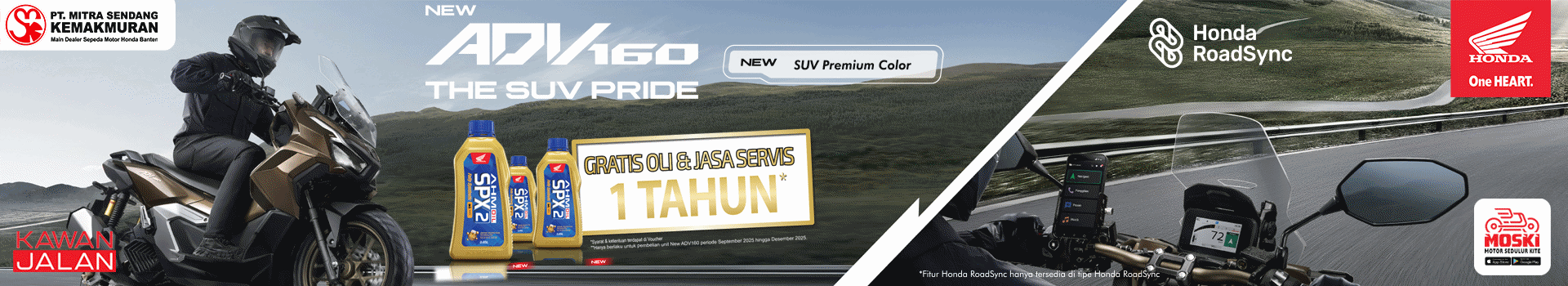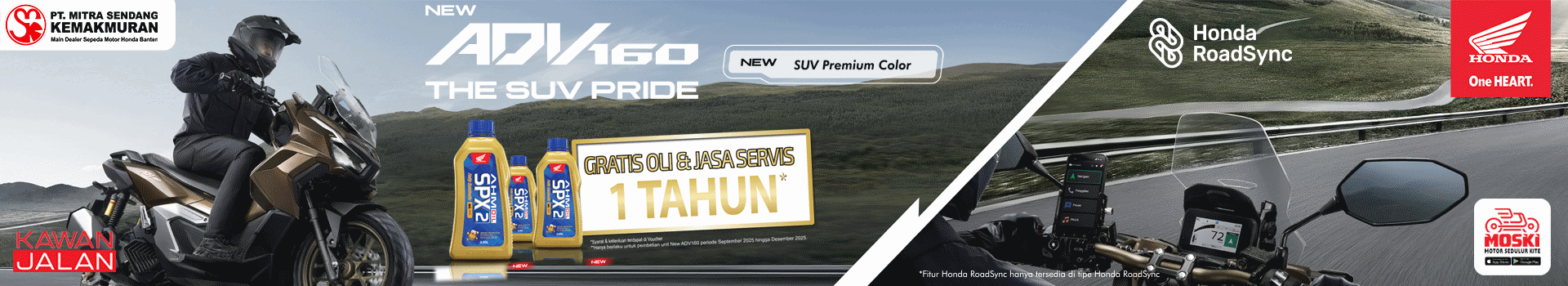BISNISBANTEN.COM – Tema queer bukan tamu baru di sastra Indonesia. Sejak Saman (1998) karya Ayu Utami meledak dengan campuran seksualitas, agama, dan politik, pembaca diperlihatkan bagaimana tubuh yang tidak sepenuhnya patuh pada norma heteroseksual selalu berada di persimpangan kuasa: gereja, negara, keluarga, dan kapital.
Beberapa tahun kemudian, Garis Tepi Seorang Lesbian karya Herlinatiens membuka suara lesbian dari sudut pandang orang pertama. Novel ini memotret bagaimana menjadi queer berarti terus-menerus bernegosiasi dengan keluarga dan agama, sering kali dengan harga keterasingan yang mahal. Di jalur yang lebih melodramatis, Andrei Aksana lewat Lelaki Terindah menulis roman gay yang penuh gejolak: cinta sesama jenis berhadapan frontal dengan tuntutan “normalitas” keluarga dan masyarakat.
Gelombang berikutnya hadir lebih halus namun tidak kurang tajam. Norman Erikson Pasaribu, lewat kumpulan cerpen Happy Stories, Mostly, memperlihatkan pengalaman queer Katolik di Indonesia dengan humor getir dan elemen spekulatif. Di luar Indonesia, penulis Asia Tenggara seperti Alfian Sa’at dalam Malay Sketches menyajikan potongan hidup kelas menengah Melayu—termasuk tokoh-tokoh queer—yang bernafas di bawah bayang-bayang negara dan norma komunitas.
Dari deretan ini, banyak yang bertumpu pada dua tenaga besar: perlawanan dan tragedi. Tokoh queer atau menggugat langsung institusi, atau berakhir remuk sebagai korban. Di titik inilah duologi Pohon-pohon yang Ditanam setelah Luka dan Laki-laki yang Membawa Pohon di Dalam Dada karya Setiawan Chogah menawarkan jalur lain: lebih tenang, lebih domestik, dan sangat dekat dengan lanskap Banten.
Raif, Rangga, dan Cinta yang Tidak Mencari Panggung
Dua novel ini bertemu di satu poros: Raif. Di buku pertama, kita bertemu Raif di sebuah rumah putih di Serang, dengan halaman, pancuran bambu, dan Ficus virens yang menjadi metafora besar luka yang ditanam. Di sana ada Rangga, Dinda, dan Keira—sebuah keluarga aparat yang nyaris runtuh oleh kebohongan, kelelahan, dan rasa bersalah—dan Raif hadir sebagai orang luar yang ikut menyelamatkan rumah itu.
Di buku kedua, fokus bergeser ke dalam dada Raif. Ia meninggalkan Serang, mengajar kelas literasi finansial di Hong Kong, lalu membangun hidup bersama Ziraf. Di sela itu, ada rasa yang tidak pernah benar-benar padam terhadap Rangga; rasa yang tidak bisa lagi disamaratakan dengan istilah “persahabatan biasa”.
Setiawan memilih untuk tidak menjadikan hubungan Raif–Rangga sebagai skandal. Tidak ada adegan yang sengaja didesain untuk “memancing amarah moral”. Yang diceritakan justru hal-hal yang tampak biasa: pesan WhatsApp yang dibiarkan abu-abu empat tahun, pelukan singkat di bawah flamboyan KP3B Serang, syukuran rumah baru di kompleks perumahan yang tenang. Di dalam ruang-ruang itulah isu orientasi bekerja: tidak berteriak, tapi pelan-pelan mengubah cara tokoh-tokoh ini memaknai komitmen, kesetiaan, dan pulang.
Raif dan Rangga bukan tokoh queer yang sedang mencari panggung. Raif tidak memakai orientasinya untuk menggugat institusi agama secara terbuka. Rangga tidak menjadikan relasinya dengan Raif sebagai alasan menghancurkan rumah tangganya. Yang mereka lakukan justru sebaliknya: mengakui bahwa rasa itu ada, lalu mencari bentuk hidup yang paling sedikit merusak Dinda dan Keira.
Narasi seperti ini jarang muncul. Dalam banyak novel, orientasi non-heteroseksual sering menjadi tiket menuju dua ujung: penolakan total atau perayaan agresif. Duologi Setiawan menolak kedua ekstrem itu. Raif mencintai Rangga dan tetap memilih menjauh agar Rangga bisa utuh sebagai suami dan ayah. Rangga mencintai Raif dan tetap memutuskan tinggal, menua, dan membesarkan Keira bersama Dinda. Cinta yang tidak berujung kepemilikan, tapi juga tidak dinafikan.
Orientasi yang Tak Bisa “Disembuhkan”, Iman yang Tidak Pergi
Daya dobrak utama duologi ini justru ada pada cara ia menggabungkan iman dan orientasi. Raif digambarkan sebagai sosok yang salah satu kakinya selalu menjejak di ruang intelektual: ia membaca, menulis, mengajar soal finansial dengan konsep-konsep yang rapi. Di sisi lain, ia juga teguh beribadah; bacaan fikih dan tradisi keagamaannya tidak dangkal.
Dengan latar seperti itu, Setiawan seakan sengaja menggugurkan asumsi ringan yang sering beredar: bahwa orientasi “menyimpang” hanya terjadi karena kurang ilmu, kurang iman, atau “pergaulan salah”. Raif punya semua bekal itu; ia bukan korban tontonan, bukan pula orang yang tidak pernah bertanya kepada dirinya sendiri. Namun rasa terhadap Rangga tetap hadir dan tidak lenyap hanya karena ia salat lebih khusyuk.
Rangga pun bukan aparat polos yang tidak mengerti konsekuensi. Ia tahu persis garis batas profesi, reputasi, dan risiko sosial yang mengintai. Ketika ia akhirnya memilih menetap bersama Dinda dan Keira, pilihan itu bukan karena tiba-tiba “sembuh”, melainkan karena ia sadar ada tanggung jawab yang lebih besar ketimbang memuaskan rindunya sendiri.
Dengan konfigurasi tokoh semacam ini, duologi Setiawan mengajak pembaca menghentikan kalimat-kalimat gampang seperti “asal mau, pasti bisa sembuh”. Bukan karena penulis sedang mempromosikan bahwa semua hubungan sah-sah saja, melainkan karena realitas jauh lebih berlapis. Pertanyaannya bergeser: kalau rasa itu tidak bisa dihapus, bagaimana kita memastikan bahwa ia tidak menjelma tindakan yang merampas hak orang lain?
Iman dalam dua novel ini tidak tampil sebagai palu yang memukul bersalah. Ia hadir sebagai meja tempat semua luka diletakkan dulu, baru kemudian diputuskan akan dibawa ke mana. Raif tidak membuang keyakinannya; ia menggunakannya untuk bertanya: “Langkah mana yang paling sedikit menambah korban?”
Satire Halus terhadap Cara Kita Menghukum
Terdapat lapisan kritik sosial yang tidak pernah diucapkan gamblang, tetapi mudah dibaca. Bila kita bersikeras menyebut homoseksualitas sebagai sesuatu yang “tidak normal”, duologi ini diam-diam menanyakan: mengapa korupsi, kekerasan rumah tangga, penganiayaan, atau perselingkuhan terang-terangan—yang jelas-jelas merugikan orang lain—tidak selalu disorot dan dihukum setajam itu?
Setiawan tidak menjawab dengan khutbah panjang. Ia menampilkan tokoh-tokoh yang dalam kacamata masyarakat sering kita letakkan di podium: aparat, penulis, pengajar, “orang baik”, “orang alim”. Mereka semua ditempatkan sebagai manusia yang rapuh dan bisa keliru, entah orientasinya apa. Dengan begitu, standar moral pembaca digeser pelan-pelan: bukan dari siapa yang “normal”, tetapi dari siapa yang siap bertanggung jawab atas dampak pilihannya.
Pada saat yang sama, duologi ini menjauh dari jebakan lain: menjadikan tokoh queer sebagai alat untuk mengemis simpati. Raif tidak dipoles sebagai korban suci; ia juga menyakiti orang lain lewat diam empat tahun kepada Rangga dan Dinda. Pilihan-pilihannya mengundang kritik, bukan hanya empati. Di titik itulah novel ini terasa jujur: ia tidak sedang meminta pembaca “setuju”, melainkan meminta pembaca melihat manusia di balik label.
Banten sebagai Latar: Queer, Iman, dan Kehidupan Sehari-hari
Untuk pembaca Banten, ada satu lapisan lagi yang membuat duologi ini terasa dekat: lokasinya. Serang, KP3B, kultur aparat, komunitas istri anggota, sampai kelas-kelas kecil literasi finansial—semuanya sangat lokal. Di tengah isu queer yang sering dianggap “isu kota besar” atau “isu luar negeri”, Setiawan meletakkannya di halaman rumah, masjid lingkungan, dan kantor-kantor di Banten.
Azan magrib, pengajian, syukuran rumah baru, bahkan obrolan ringan tentang uang muka rumah dan biaya sekolah anak, menjadi panggung di mana iman dan orientasi saling berhadapan tanpa gaduh. Raif dan Rangga tidak hidup di dunia abstrak; mereka hidup di Serang, dengan ritme dan tekanan sosial yang pembaca bisnisbanten.com kenal betul.
Pilihan ini penting. Ia menunjukkan bahwa pembicaraan soal queer tidak melulu berlangsung di kafe Jakarta atau dalam wacana akademik yang jauh. Ia juga terjadi di ruang tamu rumah di Serang, di teras rumah dinas di kawasan kantor pemerintahan, di antara piring nasi dan gelas teh.
Pada saat yang sama, keberadaan Raif sebagai pengajar literasi finansial dan Raif–Ziraf yang kemudian memilih Singapura sebagai basis kerja menunjukkan bahwa orang-orang dengan identitas kompleks ini juga ikut bergerak di arus ekonomi global: bekerja, mengajar, membangun usaha, merancang proyek sosial. Mereka bukan sekadar tema diskusi; mereka ikut memutar roda ekonomi dan kehidupan sosial.
Tidak Ada yang Menang, Tidak Ada yang Dihapus
Kalau banyak fiksi queer ditutup dengan dua pola—pemberontakan besar atau tragedi besar—duologi Setiawan Chogah memilih akhir yang lebih “sederhana”, tapi justru terasa lebih dewasa.
Rangga dan Dinda tetap bersama, membesarkan Keira di rumah baru. Raif membangun hidupnya bersama Ziraf di kota lain, dengan komitmen untuk tidak hilang lagi tanpa kabar. Rumah lama di Serang dijadikan ruang belajar, bukan monumen luka. Tidak ada pihak yang diumumkan sebagai “pemenang”; tidak ada pula yang dihapus dari sejarah pribadi masing-masing.
Dalam peta sastra queer Indonesia, posisi ini menarik. Ia menggeser fokus dari pertanyaan “apakah ini boleh?” ke pertanyaan “bagaimana kita hidup dengan luka dan orientasi yang tidak bisa dihapus, tanpa menambah korban baru?”. Di tengah kegaduhan wacana tentang iman dan tubuh, duologi ini memilih sikap yang sunyi, tetapi tegas: tidak semua persoalan bisa dibereskan dengan vonis cepat, dan tidak semua luka perlu diobati dengan menyuruh orang melupakan dirinya sendiri.
Bagi pembaca di Banten, mungkin justru di situ relevansinya: bahwa di balik jargon, spanduk, dan debat publik, ada orang-orang nyata—dengan seragam, dengan mukena, dengan slip gaji, dengan cicilan KPR—yang diam-diam bergulat dengan hal-hal serupa. Duologi ini tidak menawarkan resep, tetapi menawarkan cermin yang jujur.
Dan mungkin, itu yang paling dibutuhkan: bukan jawaban hitam putih, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa iman dan orientasi bisa saja hidup berdampingan, saling mengawasi, saling mengingatkan, tanpa harus saling meniadakan.